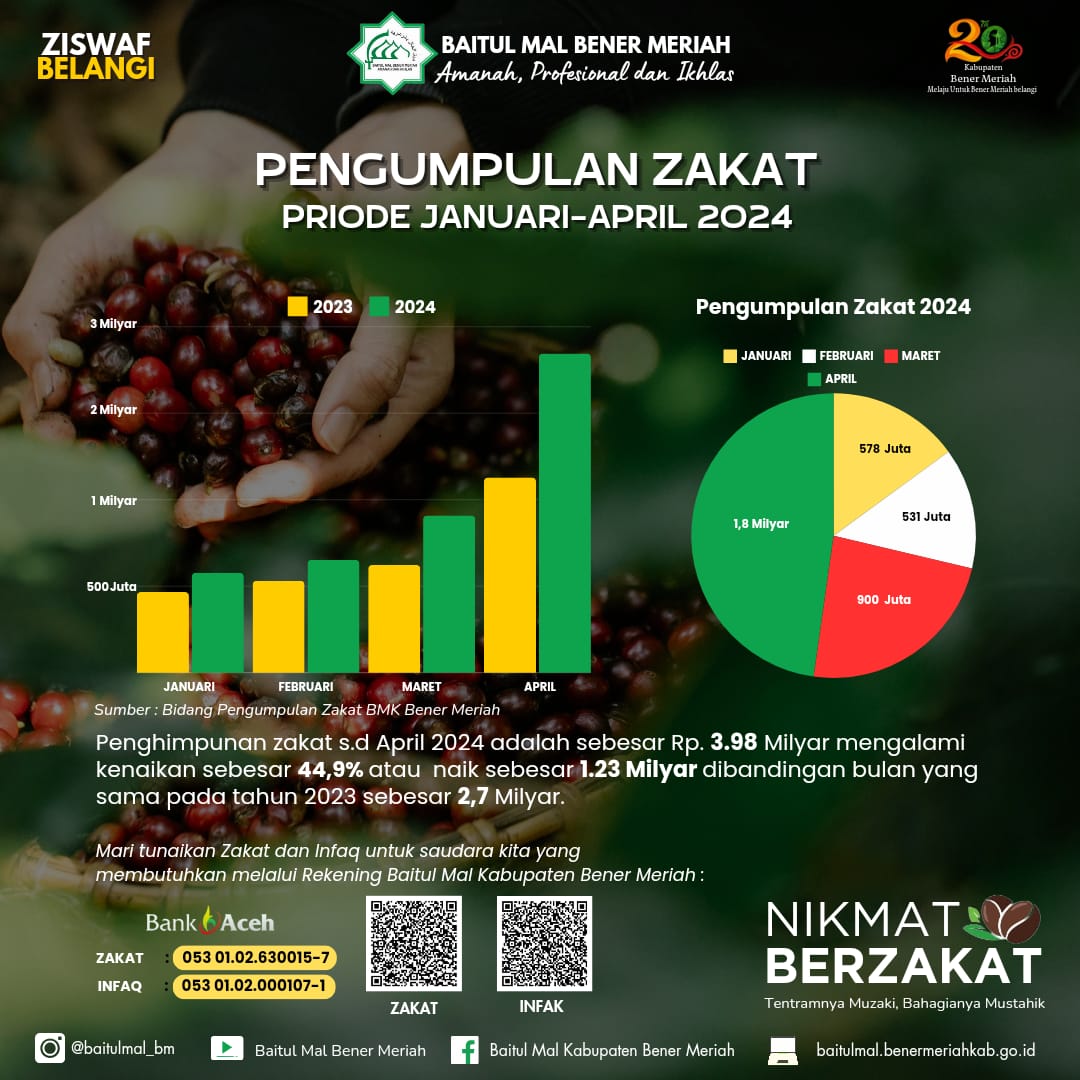Bireuen – detikperistiwa.co.id
Tradisi Makmeugang tetap hidup dan mengakar kuat di tengah masyarakat Aceh sebagai salah satu penanda penting dalam menyambut hari-hari besar Islam. Tradisi ini tidak sekadar identik dengan kegiatan memasak daging, tetapi juga sarat nilai kebersamaan, kepedulian sosial, serta rasa syukur yang diwariskan turun-temurun.
Makmeugang dilaksanakan menjelang bulan suci Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Pada momen tersebut, masyarakat berbondong-bondong membeli daging sapi atau kambing di pasar untuk dimasak dan disantap bersama keluarga. Tidak sedikit pula warga yang membagikan sebagian daging kepada tetangga, kerabat, serta masyarakat kurang mampu dan anak yatim.
Tudan—sapaan akrab Ramadhan Harun—yang merupakan anggota bidang pustaka Majelis Adat Aceh (MAA) Bireuen sekaligus tokoh masyarakat, menegaskan bahwa Makmeugang bukan sekadar tradisi kuliner, melainkan simbol kepedulian sosial masyarakat Aceh.
Menurut penuturannya, istilah Makmeugang atau Meugang berasal dari bahasa Aceh yang terdiri dari dua kata, yakni makmu yang berarti makmur dan gang yang berarti pasar. Secara harfiah, Makmeugang dapat dimaknai sebagai “pasar yang makmur” atau hari pasar yang penuh keberkahan, karena pada waktu itu aktivitas jual beli meningkat dan masyarakat memiliki semangat berbagi.
Secara historis, tradisi Makmeugang telah ada sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-17, khususnya pada era pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607–1636 M). Pada masa tersebut, sultan memerintahkan pemotongan hewan ternak dalam jumlah besar untuk kemudian dibagikan kepada rakyat secara gratis, terutama kepada kaum dhuafa.
Kebijakan itu dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas kemakmuran kerajaan sekaligus bentuk terima kasih kepada rakyat. Dari sinilah nilai berbagi dan kepedulian sosial dalam Makmeugang mulai tumbuh dan mengakar di tengah masyarakat.
Seiring waktu, tradisi tersebut tidak lagi bergantung pada kerajaan, melainkan dilanjutkan secara mandiri oleh masyarakat. Makmeugang kemudian menjadi tradisi kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi dan menjelma sebagai identitas budaya Aceh.
Pelaksanaannya yang berlangsung satu hingga dua hari sebelum hari besar keagamaan dimaknai sebagai persiapan lahir dan batin. Selain menyiapkan hidangan terbaik bagi keluarga, masyarakat juga menjadikan Makmeugang sebagai sarana mempererat silaturahmi, memperkuat solidaritas sosial, serta menumbuhkan semangat berbagi kepada sesama.
Suasana pasar daging saat Makmeugang biasanya dipadati pembeli. Permintaan yang meningkat kerap memengaruhi harga daging, namun antusiasme masyarakat tetap tinggi. Bagi banyak warga, Makmeugang adalah tradisi yang memiliki nilai emosional dan spiritual, sehingga tetap dijalankan meski kondisi ekonomi berbeda-beda.
Tudan menilai, kekuatan utama Makmeugang terletak pada nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Tradisi ini mengajarkan bahwa kebahagiaan menyambut hari besar tidak hanya dirasakan sendiri, tetapi juga dibagi kepada orang lain.
“Makmeugang adalah warisan budaya yang menjaga semangat berbagi dan memperkuat hubungan sosial masyarakat Aceh. Inilah yang membuatnya tetap bertahan hingga sekarang,” tergambar dari penjelasannya.
Dengan nilai religius, sosial, dan budaya yang menyatu, Makmeugang terus menjadi simbol kebersamaan masyarakat Aceh dalam menyambut hari-hari besar keagamaan, sekaligus pengingat pentingnya rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama.
(Erna)