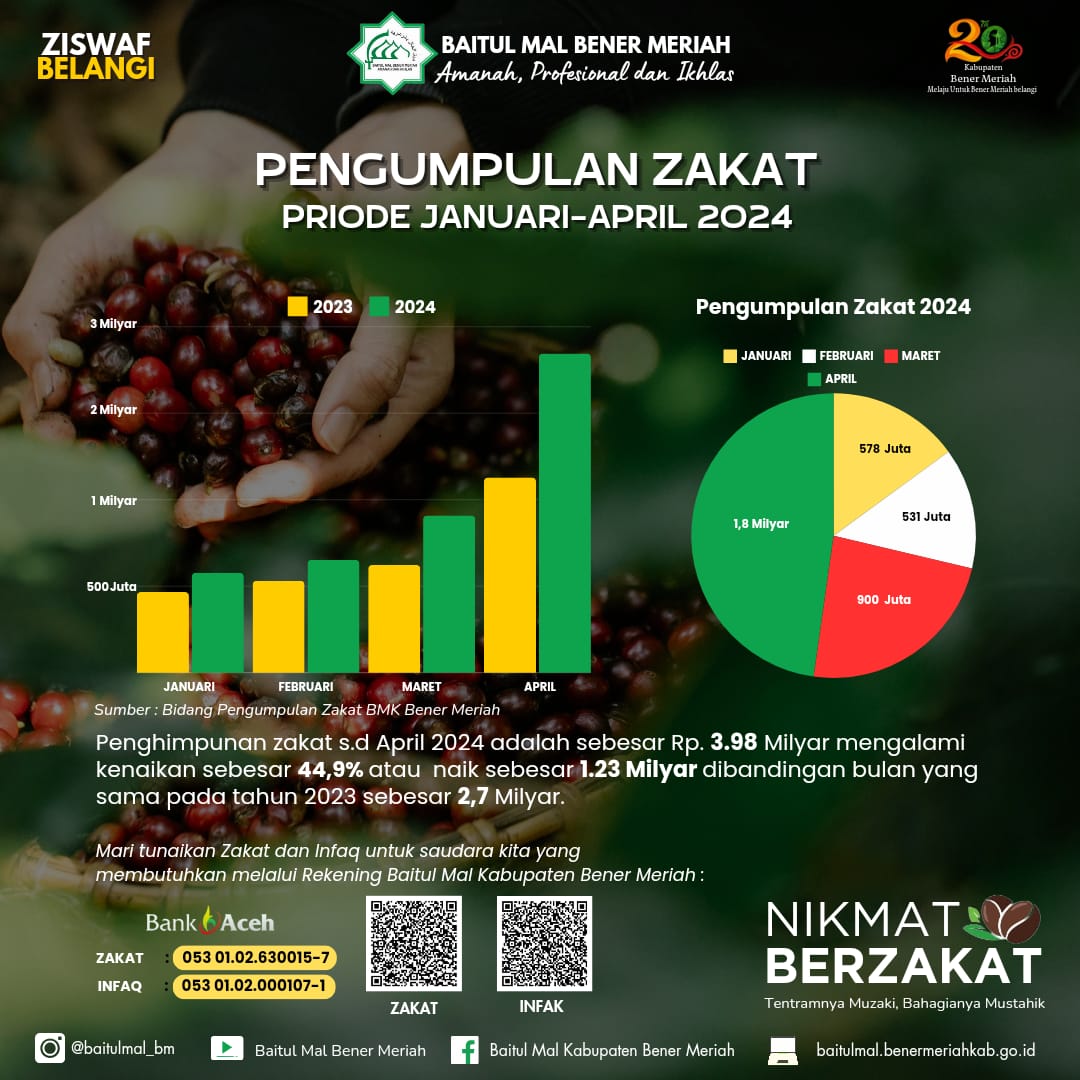Batam – detikperistiwa.co.id
Bagi sebagian orang, kelam hanyalah sebutan bagi langit yang muram atau warna yang kehilangan cahaya. Ia sering menjadi metafora bagi kesedihan, kelesuan, atau ketidakpastian. Namun, bagi saya, kelam adalah sebuah ruang batin yang sempit, di mana pikiran terkurung dalam pusaran yang tak berujung, logika kehilangan arah, dan sisa cahaya seakan berjuang mati-matian untuk sekadar bertahan hidup.
Kelam bukan sekadar keadaan fisik yang tertangkap mata, melainkan sebuah lanskap makna yang luas, sering kali hadir dalam karya sastra sebagai peringatan, bukan hiburan. Ia menyelinap ke dalam prosa dan puisi, menguji kesadaran, dan memaksa kita menatap kebenaran yang sering kita hindari.
Dalam Goresan Terbagi Kelam, kelam adalah panggilan lirih namun tegas: kembali kepada Tuhan sebelum gulungan waktu menelan seluruh kesempatan. Ia menolak menjadi mantera kosong dari ampas kebiasaan sesat. Di sini, kelam adalah teguran yang tak mengenal basa-basi, peringatan bahwa pusaran kesalahan akan semakin menguat jika dibiarkan.
Di Menanti Gulai Hitam, kelam menjadi ironi yang manis-pahit. Gulai hitam itu bukan sekadar hidangan, melainkan simbol penantian sia-sia. Harapan yang tak mungkin tercapai hanyalah melahirkan kehampaan, dan kelam adalah tirai yang menutup setiap pintu keluar dari kekecewaan itu.
Remukan Bah Keledai membawa kelam ke ranah peringatan moral. Tubuh yang tampak perkasa dari luar bisa saja lapuk di dalam. Peringatan Al-Qur’an tentang buruknya suara keledai mengandung pesan agar kita tidak melangkah dengan keangkuhan, dan tidak mengumbar suara kesombongan yang menyingkirkan kebijaksanaan.
Sementara itu, Sembarangan adalah kelam yang tak memberi kesempatan kedua. Ia hadir sebagai bendera kuning yang berkibar di depan rumah, menandai akhir sebuah perjalanan hidup. Pesannya sederhana namun dalam: setiap kecerobohan adalah undangan terbuka bagi kesudahan yang datang terlalu cepat.
Kelam, dalam berbagai wajahnya, adalah guru yang keras namun adil. Ia menuntut kesadaran penuh, kewaspadaan, dan kerendahan hati dalam menjalani hidup. Sebab, ketika kita terlalu lama tinggal dalam gulitanya, barangkali cahaya yang tersisa tak lagi mampu menembus pekat yang telah kita pelihara sendiri. (Nursalim Turatea).