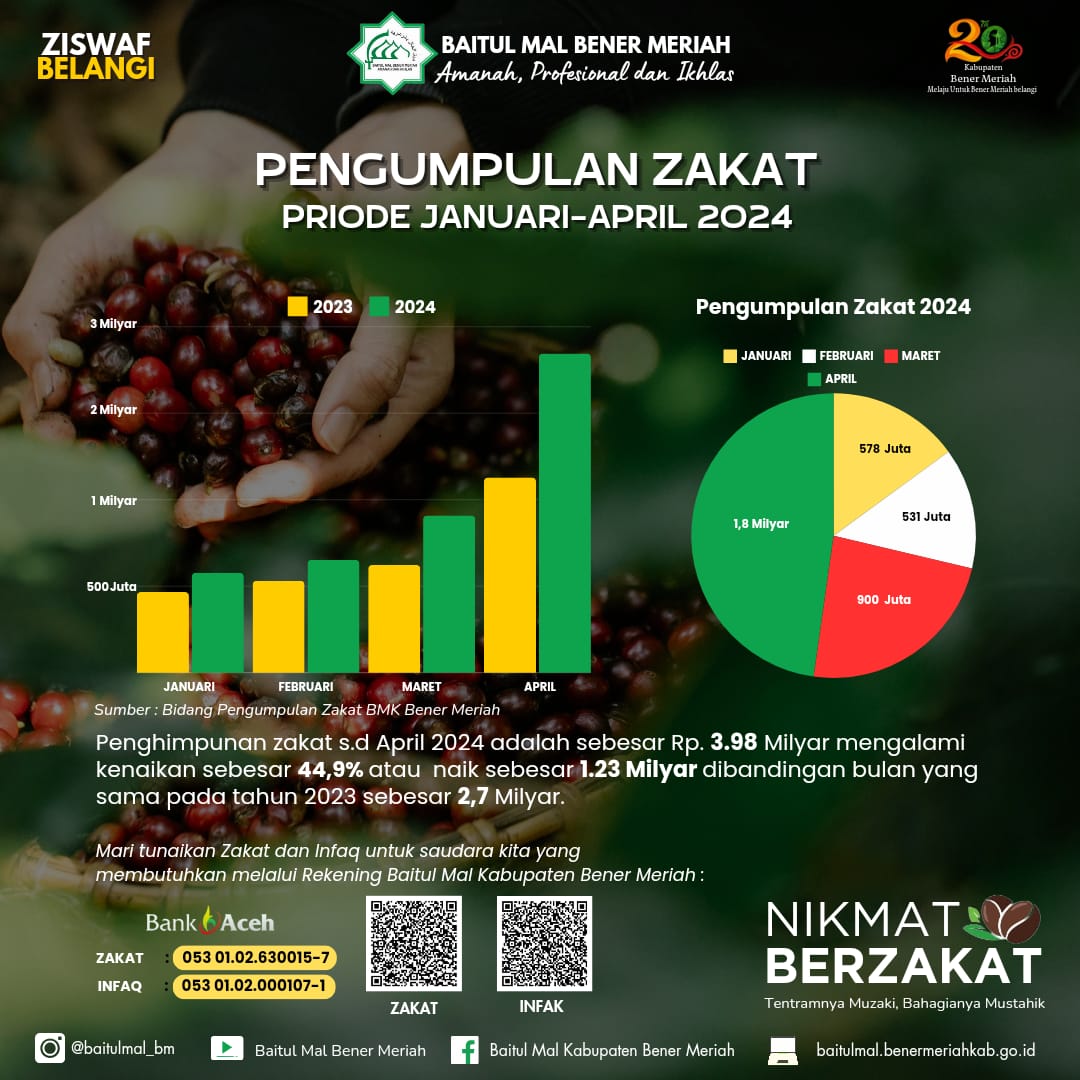Aceh | detikperistiwa.co.id
Meski Gubernur Aceh telah meminta bantuan dunia internasional, Presiden Prabowo Subianto tetap bergeming. Pemerintah pusat belum menetapkan status bencana nasional, dengan alasan situasi dinilai masih terkendali dan Indonesia dinyatakan mampu menangani sendiri tanpa perlu membuka status tersebut.
Dalam pernyataannya, Presiden menyebut bencana yang terjadi “baru” melanda tiga provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Pemerintah, kata dia, masih memiliki kapasitas nasional untuk merespons tanpa harus menetapkan status bencana nasional.
Namun, pernyataan itu berhadapan langsung dengan realitas lapangan. Berdasarkan data resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana per 16 Desember 2025, jumlah korban jiwa akibat banjir dan bencana ikutan telah mencapai 1.030 orang. Dari jumlah tersebut, Aceh mencatat duka terdalam dengan 431 korban meninggal, disusul Sumatera Utara 355 orang, dan Sumatera Barat 244 orang. Selain itu, 206 orang masih dinyatakan hilang, meninggalkan ketidakpastian panjang bagi keluarga mereka.
Selain korban jiwa, BNPB juga mencatat sekitar 7.000 orang luka-luka, lebih dari 624.000 jiwa mengungsi, serta 186.488 rumah rusak. Angka tersebut mencerminkan skala kehancuran yang melampaui sekadar gangguan sementara, dengan dampak sosial dan psikologis yang luas.
Kerusakan juga meluas pada fasilitas publik. Sebanyak 219 fasilitas kesehatan terdampak, 967 fasilitas pendidikan rusak, dan 434 rumah ibadah ikut terkena dampak. Tak hanya itu, 290 gedung perkantoran dan 145 jembatan dilaporkan rusak atau ambruk, memutus akses dan memperlambat distribusi bantuan di sejumlah wilayah.
Di tengah kondisi tersebut, muncul perbedaan sikap antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat menegaskan prinsip kemandirian nasional dan kehati-hatian membuka bantuan luar negeri. Sebaliknya, Pemerintah Aceh secara terbuka meminta dukungan internasional dengan menyurati United Nations Development Programme dan United Nations Children’s Fund—dua lembaga PBB yang memiliki rekam jejak kuat dalam penanganan krisis kemanusiaan di Aceh pascatsunami 2004.
Permintaan tersebut dilatarbelakangi keterbatasan di lapangan: infrastruktur yang hancur, pengungsi yang terus bertambah, serta tekanan berat pada logistik dan layanan dasar. Di saat yang sama, bantuan dari Malaysia dan Tiongkok mulai berdatangan, dan relawan internasional dilaporkan bersiap turun ke lokasi terdampak.
Seorang pengungsi di Aceh menggambarkan kondisi lapangan dengan nada getir. “Biasanya banjir seminggu sudah surut, rumah bisa ditempati lagi. Ini banjir lumpur setinggi dada, bahkan ada rumah yang tertimbun lumpur. Tidak bisa lagi ditempati,” ujarnya.
Perbedaan narasi pun kian mengemuka. Dari Jakarta terdengar keyakinan bahwa negara mampu berdiri sendiri. Dari daerah terdampak terdengar kebutuhan mendesak akan tambahan bantuan. Kedua pandangan tersebut berangkat dari sudut yang berbeda: satu dari kapasitas negara, satu lagi dari daya tahan masyarakat di lapangan.
Tidak menetapkan status bencana nasional mungkin sah secara administratif dan strategis. Namun, data BNPB menunjukkan bahwa penolakan terhadap status tersebut tidak otomatis berarti penderitaan warga telah tertangani sepenuhnya. Angka korban jiwa, pengungsi, dan kerusakan infrastruktur menjadi pengingat bahwa skala krisis terus berkembang.
Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas menegaskan bahwa perdebatan ini seharusnya tidak berhenti pada soal gengsi atau kemandirian. “Negara besar bukan diukur dari keberanian menolak bantuan, melainkan dari kecepatan dan ketepatan menyelamatkan rakyatnya,” ujarnya.
Pada akhirnya, pertanyaan yang mengendap di lapangan bukan semata apakah negara mampu berdiri sendiri, melainkan apakah negara cukup cepat hadir bagi warganya yang masih bergelut dengan lumpur, kehilangan, dan harapan yang menipis.
By AM