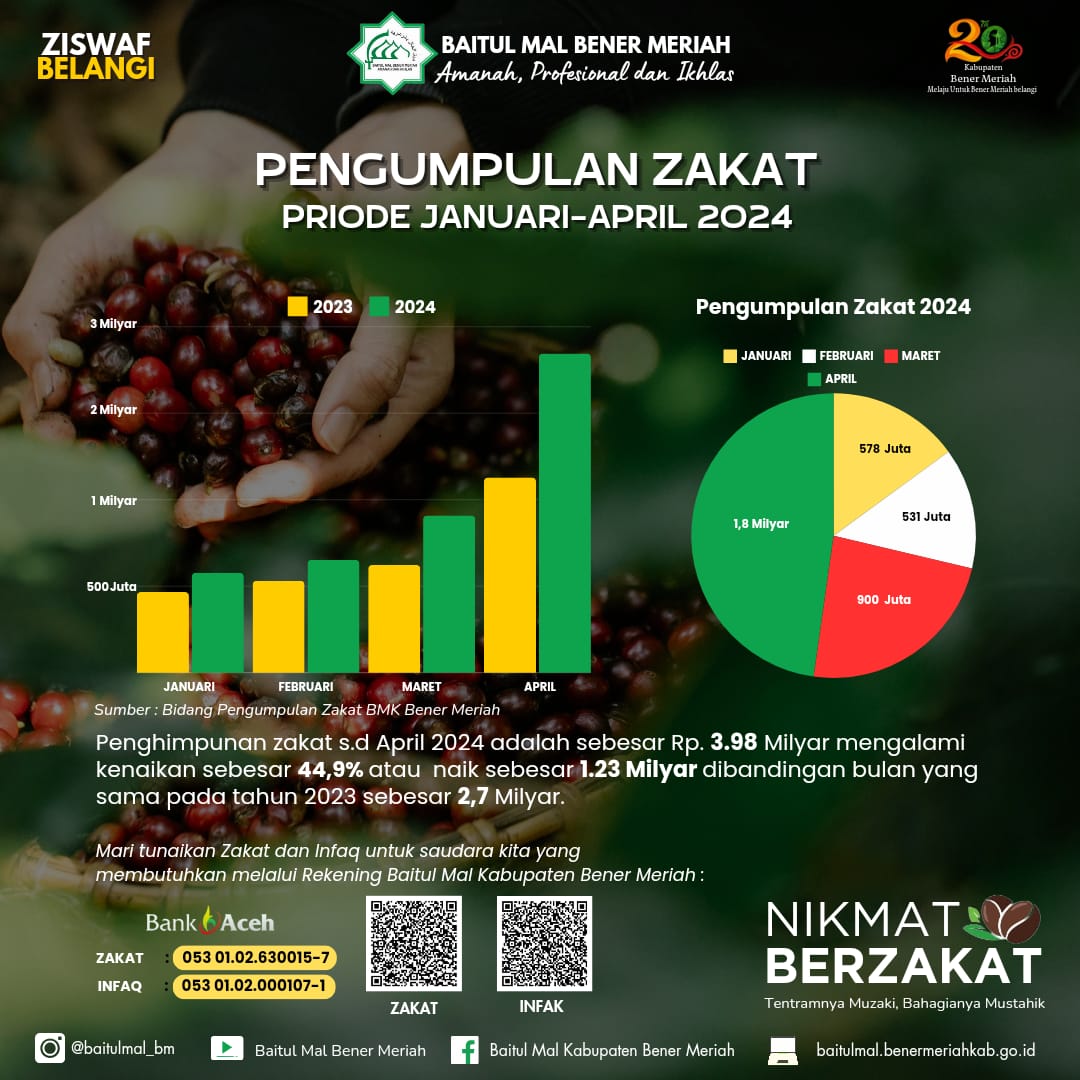Spektakuler! Inilah Tradisi Merti Desa Limbangan yang Sudah Berusia 393 Tahun

LIMBANGAN –Https//detikperistwa.co.id Saat matahari baru menyentuh pucuk-pucuk pohon, riuh warga mulai terdengar di tepian sendang. Ember dan sapu tak hanya membawa air, tanah dan daun, tapi juga harap: agar tanah kelahiran mereka tetap tenteram. Hari itu, Selasa (29/4) Merti Desa Limbangan kembali digelar, tradisi tahunan yang telah berumur nyaris empat abad.
Di tengah zaman yang berlari cepat, Desa Limbangan, Kecamatan Limbangan, Kendal, masih setia menjaga denyut masa silam. Merti Desa bukan sekadar peringatan hari lahir. Ia adalah serangkaian laku budaya yang menyatukan doa, sejarah, dan kesenian, berlangsung turun-temurun sejak 393 tahun silam.
“Dimulai hari ini dengan bersih-bersih sendang,” ujar Lurah Limbangan, Munjiyah, di sela kegiatan. “Lalu dilanjutkan bedah pikat, mencari hewan sebagai bagian dari syukuran untuk acara pagelaran wayang .”
Ritual berlanjut dengan malem Jumat tahlilan di makam Mbah Ki Ageng Mataram, tokoh spiritual yang dipercaya sebagai leluhur desa. Siang hari, masyarakat

berbondong-bondong mengikuti arak-arakan Gunungan, yang berjalan dari Lapangan Limbangan menuju Masjid Baitur Rahim, sebagai bagian dari Grebeg Gunungan.
Menjelang senja, digelar ruwatan—prosesi tolak bala untuk membersihkan diri secara spiritual. Dan ketika malam tiba, pentas wayang kulit digelar sebagai puncak hiburan sekaligus simbol kebijaksanaan Jawa.
“Tahun ini, tiga grup kuda lumping dari Magelang, Temanggung, dan Limbangan juga tampil. Ini bentuk hiburan rakyat sekaligus pelestarian budaya,” kata Chandra Putra, Ketua Panitia Merti Desa sekaligus Camat Singorojo. Ia bukan orang baru. Sang ayah dahulu juga memegang peran yang sama, menjadikan tanggung jawab ini lebih dari sekadar jabatan—tapi warisan.
Merti Desa tak dibangun dalam semalam. Persiapan dimulai lebih dari sebulan sebelumnya. Rapat demi rapat digelar, panitia dibentuk, anggaran disusun. Warga terlibat aktif—ada yang menyumbang tenaga, ada yang memasak, ada pula yang iuran uang. Gotong royong menjadi nadi utama.
“Semua ini swadaya. Warga menyumbang seikhlasnya—nasi bungkus, waktu, bahkan hanya semangat pun kami syukuri,” tambah Chandra.
Di tengah kencangnya arus modernitas, Limbangan memilih menoleh ke belakang. Bukan untuk mundur, melainkan untuk menyerap akar kekuatan budaya, menjaga keseimbangan antara yang gaib dan nyata, antara manusia dan alam.
Puncak acara akan berlangsung pada Jumat Pahing hingga Sabtu Kliwon, hari-hari yang diyakini membawa energi spiritual kuat. Di situlah seluruh rangkaian ditutup, dengan satu doa besar yang diaminkan ratusan orang: semoga desa ini tetap lestari, masyarakatnya makmur, dan budayanya tak pernah luntur.

Penulis: A.pram